PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA SISTEMATIK PENDIDIKAN
DEMOKRASI.
1.) Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education,
secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas
dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu
sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan
nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di
sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di
perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatun crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Pengalaman tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1975, di Indonesia kelihatannya terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi civics, pendidikan kewargaan negara, dan pendidikan IPS.
perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatun crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Pengalaman tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1975, di Indonesia kelihatannya terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi civics, pendidikan kewargaan negara, dan pendidikan IPS.
Hal itu tampak dalam penggunaan ketiga istilah itu secara bertukar-pakai.
Selanjutnya, dalam Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang
diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada
tahun 1984, sebagai pengganti mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara mulai
diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan
materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) atau "Eka Prasetia Pancakarsa". Perubahan itu
dilakukan untuk mewadahi missi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR
No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4
(Depdikbud:1975a, 1975b, 1975c). Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib mulai
dari kelas I SD s/d kelas III SMA/Sekolah Kejuruan dan keberadaannya terus
dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan
penyempurnaan Kurikulum tahun 1975. Di dalam Undang-Undang No 2/1989 tentang
Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang antara lain Pasal 39,
menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan
materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif
atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila.
Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang
dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk
mata pelajaran Civics atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara
fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah
terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan
telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis
operasional kurikuler.
Krisis atau dislocation menurut pengertian Kuhn (1970) yang bersifat konseptual
tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: civics tahun 1962 yang
tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari
pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial;
PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan
MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975
dan 1984 yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994
sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang
tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila
dan P4. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format
buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang
belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan
konsep. Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap
diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya
pelaksanaan metode pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya
suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan
dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional. Kini pada
era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan
tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi
konstitusional yang lebih murni, keberadaan dan jati diri mata pelajaran PPKn
kembali dipertanyakan secara kritis. Dalam status kedua, yakni sebagai mata
kuliah umum (MKU) pendidikan kewarganegaraan diwadahi oleh mata kuliah
Pancasila dan Kewiraan. Mata kuliah Pancasila bertujuan untuk mengembangkan
wawasan mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa Indonesia, sedangkan kewiraan, yang mulai tahun 2000 namanya berubah
menjadi Pendidikan Kewarganegaran, bertujuan untuk mengembangkan wawasan
mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban
warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945.
Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh
mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan
Kepribadian atau MKPK. Dalam status ketiga, yakni sebagai pendidikan disiplin
ilmu (Somantri:1998), pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan
disiplin ilmu sosial sebagai program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan di LPTK (IKIP/ STKIP/ FKIP) Jurusan atau Program Studi Civics
dan Hukum pada tahun 1960-an, atau Pendidikan Moral Pancasila dan
Kewarganegaraan (PMPKn) pada saat ini. Bila dikaji dengan cermat, rumpun mata
kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam program pendidikan guru tersebut pada
dasarnya merupakan program pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial bidang
pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual pendidikan disiplin ilmu ini
memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu politik, sebagai
substansi induknya. Secara kurikuler program pendidikan ini berorientasi kepada
pengadaan dan peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan
kewarganegaraan. Dampaknya, secara akademis dalam lembaga pendidikan tinggi
keguruan itu pusat perhatian riset dan pengembangan cenderung lebih terpusat
pada profesionalisme guru. Sementara itu riset dan pengembangan epistemologi pendidikan
kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan, belum banyak mendapatkan
perhatian. Dalam status keempat, yakni sebagai crash program pendidikan politik
bagi seluruh lapisan masyarakat, Penataran P-4 mulai dari Pola 25 jam sampai
dengan Pola 100 jam untuk para Manggala yang telah berjalan hampir 20 tahun
dengan Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan P-4 atau BP7 Pusat dan Propinsi
sebagai pengelolanya, dapat dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan
kewarganegaraan yang bersifat non-formal.
Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi melalui gerakan
reformasi baru-baru ini, dan juga dilandasi oleh berbagai kenyataan sudah
begitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru, tidak
dapat dielakkan tudingan pun sampai pada Penataran P-4 yang dianggap tidak
banyak membawa dampak positif, baik terhadap tingkat kematangan berdemokrasi
dari warganegara, maupun terhadap pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Sebagai implikasinya, sejalan dengan jiwa dan semangat Ketetapan MPR Nomor
XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, kini semua bentuk
penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi
dilikuidasi.
Kini tumbuh kebutuhan baru untuk mencari bentuk pendidikan politik dalam
bentuk pendidikan kewarganegaraan yang lebih cocok untuk latar pendidikan non
formal, yang diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kedewasaan seluruh
warganegara yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan
cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan
adanya sistem pendidikan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, terasa
menjadi sangat mendesak.Dalam status kelima, yakni sebagai suatu kerangka
konseptual sistemik pendidikan kewarganegaraan terkesan masih belum solid
karena memang riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan
belum berjalan secara institusional, sistematis dan sistemik. Paradigma
pendidikan kewarganegaraan yang kini ada kelihatannya masih belum sinergistik.
Kerangka acuan teoritik yang menjadi titik tolak untuk merancang dan
melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam masing-masing statusnya sebagai
mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, atau sebagai program pendidikan
disiplin ilmu dan program guru, atau sebagai pendidikan politik untuk
masyarakat mengesankan satu sama lain tidak saling mendukung secara
komprehensif. Sebagai akibatnya, program pendidikan kewarganegaraan di sekolah,
di lembaga pendidikan guru, dan di masyarakat terkesan belum sepenuhnya saling
mendukung secara sistemik dan sinergistik.
1.2. Perumusan Masalah
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirasakan: rentan terhadap
pengaruh perubahan dalam kehidupan politik, tidakajek dalam sistem kurikulum
dan pembelajarannya; pendidikan gurunya yang cenderung terlalu memihak pada
tuntutan formal-kurikuler di sekolah dan kurang memperhatikan pengembangan
pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian pendidikan disiplin ilmu,
epistemologi pendidikan kewarganegaraan tidak berkembang dengan pesat;
pembelajaran sosial nilai Pancasila yang cenderung berubah peran dan fungsi
menjadi proses indoktrinasi ideologi negara, tidak kokohnya dan tidak
koherennya landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan sebagai program
pendidikan demokrasi.
2.) Kajian Literatur
Ada beberapa konsep yang dikaji, yakni jatidiri, pendidikan
kewarganegaraan, wahana sistemik, dan pendidikan demokrasi. Istilah jatidiri
diadaptasi dari characteristic dalam bahasa Inggris, yang memiliki sinonim
paling dekat dengan individuality, specialty, attribute, feature, character
(Devlin:1961), yang dapat diartikan secara bebas sebagai ciri khas atau
atribut. Dalam artikel ini jatidiri dimaksudkan sebagai ciri khas atau atribut
konseptual dan empirik dari pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik
pendidikan demokrasi. Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat
diterjemahkan menjadi pendidikan kewargnegaraan yakni civic education dan
citizenship Education. Cogan (1999:4) mengartikan civic education sebagai
"...the foundational course work in school designed to prepare young
citizens for an active role in their communities in their adult lives".
Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan
warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam
masyarakatnya. Sedangkan citizenship education atau education for citizenship
oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang
lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as
out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family,
the religious organization, community organizations, the media,etc which help
to shape the totality of the citizen".
Dalam tulisan ini istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya
digunakan dalam pengertian yang luas seperti "citizenship education"
atau "education for citizenship" yang mencakup pendidikan
kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah
dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program
penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak
pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan
atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping
itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang
kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaran
sebagai program pendidikan demokrasi.Kata sistem diserap dari Bahasa Inggris
system, yang secara harfiah artinya "susunan" (Echols dan Shadily,1975:575).
Sedangkan menurut Hornby, Gatenby, dan Wakefield (1962:1024) system diartikan
sebagai group of things or parts working together in a regular relation atau
kelompok benda-benda atau hal-hal atau bagian-bagian yang bekerjasama dalam
suatu hubungan yang teratur. Pengertian yang lebih lengkap tentang sistem
diberikan oleh Rahmat (1995:336) sebagai berikut:
1). Gabungan hal-hal yang disatukan kedalam sebuah kesatuan yang konsisten
dengan kesalinghubungan (interaksi, interdependensi, interrelasi) yang teratur
dari bagian-bagiannya.
2). Gabungan hal-hal (obyek-obyek, ide-ide, kaidah-kaidah,
aksioma-aksioma,dll) yang disusun dalam sebuah aturan yang koheren
(subordinasi, atau inferensi, atau generalisasi,dll) menurut beberapa prinsip
(atau rencana, atau rancangan, atau metode) rasional atau yang dapat
dipahami" Dalam pengertian seperti dikutip itulah penulis mengartikan
sistem. Selanjutnya, yang dimaksud dengan konteks keilmuan adalah keterpaduan
dari unsur-unsur kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan dalam arti
luas. Konsep keterpaduan itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah
integrated, seperti dalam konsep integrated social studies (Dufty:1970,
Taba:1971), yang kemudian diterjemahkan menjadi IPS Terpadu. Dengan merujuk
kepada pengertian masing-masing istilah seperti telah dibahas di muka dan
konsep keterpaduan pengetahuan atau integrated knowledge system menurut
Hartoonian (1992), maka konsep kerangka konseptual konteks keilmuan yang
digunakan diartikan sebagai tatanan pengetahuan yang terstruktur secara
paradigmatik, yang obyek telaahnya disikapi sebagai suatu kesatuan garis
berpikir dan metode kerjanya bersifat sistemik (kesatuan yang bersifat
multidimensional) dan kemanfaatannya menyangkut banyak hal yang satu sama lain
saling berkaitan.Pendidikan demokrasi yang kini dengan tegas diterima sebagai
esensi pendidikan kewarganegaraan (CICED:1999), dalam Kurikulum 1994 merupakan
bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibingkai
menjadi satu dengan nilai-nilai masing-masing sila sebagai intinya dalam
kedudukan yang setara dan interaktif. Dengan paradigma yang ada itu maka secara
substantif di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna pendidikan
Pancasila, dalam arti berlandaskan dan berorientasi pada cita-cita dan nilai yang
secara koheren dan sistemik terkandung dalam Pancasila. Dewasa ini tumbuh
gagasan yang kuat untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
utama dan esensi dari pendidikan demokrasi, sebagaimana telah menjadi salah
satu kesimpulan dari Conference on Civic Education for Civil Society
(CICED:1999). Berkaitan dengan hal itu Sudarsono (1999) menegaskan bahwa “the
ideals and values of democracy and their implementations in daily activities at
micro as well as macro levels can be regarded as the heart of civil society”.
Oleh karena itu, lebih lanjut ditekankan bahwa “...democratic living should be
fostered in order that we should be able to establish a good Indonnesian civil
society”, dan untuk itulah, ditegaskan lebih jauh lagi bahwa “... the existing
civic education both for schools and for society should be reassessed and
redesigned”. (Sudarsono:1999). Dari situ dengan tegas tampak adanya
kecenderungan yang kuat untuk menempatkan pendidikan demokrasi sebagai intinya
dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan menggunakan kerangka berpikir itu, maka
konsep pendidikan demokrasi diartikan sebagai tatanan konseptual yang
menggambarkan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan
cita-cita, nilai, prinsip, dan pola prilaku demokrasi dalam diri individu
warganegara, dalam tatanan iklim yang demokratis, sehingga pada giliranya kelak
secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat
madani Indonesia yang demokratis. Paradigma ini dijiwai oleh ethos baru
pendidikan demokrasi “eduction about democracy, through democracy, and for
democracy” (CIVITAS International,1998; QCA;1999; CICED;1999; dan APCEC:2000;
IEA-CEP;2000).
3.) Metodologi
3.1. Obyek Telaah
Obyek telaah ada dua hal: (1) Pemikiran tentang social studies, citizenship
education, civic education secara umum dan pendidikan kewarganegaraan serta
pendidikan ilmu pengetahuan sosial secara khusus, (2)Praksis penyelenggaraan
social studies, citizenship education, civic education secara umum; pendidikan
kewarganegaraan di sekolah dan di LPTK secara khusus; dan dalam site of
citizenship di negara lain dan di Indonesia.
3.2. Pendekatan Dan Metode
Sesuai Dengan Hakikat Dan Karakteristik Obyek TelaahnyaPada dasarnya
penelitian itu diterapkan pendekatan eklektrik, yakni kombinasi pendekatan
kualitatif (utama) dan kuantitatif (pendukung), yang dikemas dalam suatu survey
khusus untuk secara kualitatif menggali, mengkaji, memilih, dan
mengorganisasikan berbagai pemikiran dan praksis citizenship education, civic
education, social studies secara umum, dan pendidikan IPS dan PPKn secara
khusus, beserta konteksnya, yang telah terdokumentasikan. Untuk mendapatkan
data dan informasi digunakan teknik Studi Dokumentasi, Komunikasi interpersonal
melalui diskusi (focus discussion).
3.3. Asumsi Dan Pertanyaan
Penelitian
Penelitian ini bertolak dari beberapa a sumsi sebagai berikut :
(1) Belum adanya paradigma yang utuh tentang pendidikan kewarganegaraan
yang dapat dijadikan kerangka dasar dan sekaligus sebagai rujukan konseptual
dan operasional bagi semua bentuk program tersebut.
(2) Kini telah tumbuh kesadaran, semangat dan komitment untuk menemukan
kembali dan merevitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pendidikan
demokrasi. Dalam penelitian itu dirumuskan pertanyaan penelitian. Bagaimana
profil konseptual sistemik pendidikan kewarganegaraan dilihat dari berbagai
pemikiran para teoritisi dan persepsi praktisi pendidikanm kewarganegaraan?
4. Hasil Dan Bahasan
4.1. Istilah Teknis
Ada tiga istilah teknis yang banyak digunakan, yakni civics, civic
education, dan citizenship education. Istilah civics merupakan istilah yang
paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore pada tahun 1886 dalam
Somantri (1969) untuk menunjukkan the science of citizenship yang isinya antara
lain mempelajari hubungan antarwarganegara dan hubungan antara warganegara
dengan negara. Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata pelajaran
yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar di
Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis,
Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA (Kerr,1999).
Di Indonesia istilah civics pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA tahun
1962, kurikulum SD tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973.
Mulai pada tahun 1900-an di USA diperkenalkan istilah citizenship education dan
civic education yang digunakan secara bertukar-pakai, untuk menunjukkan program
pendidikan karakter, etika dan kebajikan (Best:1960) atau pengembangan fungsi
dan peran politik dari warganegara dan pengembangan kualitas pribadi (Somantri
1969).
Sedangkan Allen (1960) dan NCSS (Somantri:1972) menggunakan istilah
citizenship education dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai produk
keseluruhan program pendidikan atau all positive influences yang datang dari
proses pendidikan formal dan informal. Kini istilah civic education lebih
banyak digunakan di USA serta beberapa negara baru di Eropa timur yang mendapat
pembinaan profesional dari Center for Civic Education dan Universitas mitra
kerjanya di USA, untuk menunjukkan suatu program pendidikan di sekolah yang
terintegrasi atau suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sedangkan di
Indonesia istilah civic education masih dipakai untuk label mata kuliah di
Jurusan atau Progran Studi PPKN dan nama LSM Center for Indonesian Civic
Education. Istilah civic education cenderung digunakan secara spesifik sebagai
mata pelajaran dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan istilah citizenship
education cenderung digunakan dalam dua pengertian. Pertama, digunakan di UK
dalam pengertian yang lebih luas sebagai overarching concept yang di dalamnya
termasuk civic education sebagai unsur utama (Cogan,1999; Kerr: 1999; dan
QCA:1999) disamping program pendidikaan kewarganegaraan di luar pendidikan
formal seperti site of citizenship atau situs kewarganegaraan, seperti juga
dikonsepsikan sebelum itu oleh Alleh (1962) dan NCSS (1972). Kedua, digunakan
di USA, terutama oleh NCSS, dalam pengertian sebagai the essence or core atau
inti dari social studies (Barr dkk:1978; NCSS:1985;1994). Di Indonesia istilah
citizenship education belum pernah digunakan dalam tataran formal instrumentasi
pendidikan, kecuali sebagai wacana akademis di kalangan komunitas ilmiah
pendidikan IPS. Yang konsisten menggunakan istilah citizenship education atau
education for citizenship adalah UK. Sedangkan negara lain yang diketahui
menggunakannya secara adaptif adalah Netherlands. Sebagai batasan penulis
menerjemahkan civic education dan citizenship education ke dalam istilah yang
sama namun berbeda dalam cara penulisannya.
Istilah civic education diterjemahkan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan
(memakai huruf besar di awal) dan citizenship education diterjemahkan menjadi
pendidikan kewarganegaraan (semuanya dengan huruf kecil). Istilah Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) menunjuk pada suatu mata pelajaran, sedangkan pendidikan
kewarganegaraan (PKn) menunjuk pada kerangka konseptual sistemik program
pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis. Konsep pendidikan
kewarganegaraan disebut juga sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn/SPKn) yang
dapat ditulis dengan semuanya huruf besar atau huruf kecil.
4.2. Visi Secara Paradigmatik
Citizenship education memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warganegara
ang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan
formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di
UK (QCA:1998; Kerr:1999). dangkan civic education secara umum memiliki visi
formal-pedagogis untuk mendidik arganegara yang demokratis dalam konteks
pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di USA (CCE:1996). i
Indonesia, yakni PPKn memiliki visi formal-pedagogis sebagai mata pelajaran
sosial di sekolah dan perguruan tinggi sebagai wahana pendidikan nilai
Pancasila.Bertolak dari kajian teoritik dan diskusi reflektif, dirumuskan visi
pendidikan kewarganegaraan” dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan
kewarganegaraan agar berfungsi dan berperan sebagai :
(1) Program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal,
(2) Program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan
(3) Sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu
pengetahuan sosial.
Visi ini mengandung dua dimensi, yakni :
(1) Dimensi substantif berupa muatan pembelajaran(content and learning
experiences) dan obyek telaah serta obyek pengembangan.
(2) Dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi
dan aksiologi).
Khusus dalam visinya sebagai bidang kajian ilmiah pendidikan
kewarganegaraan secara epistemologis merupakan synthetic discipline
(Somantri:1998) atau integrated knowledge system (Hartoonian:1992), atau
cross-disciplinary study (Hahn dan Torney-Purta:1999), atau kajian
multidimensional (Derricott dan Cogan:1998). Penulis menempatkan pendidikan
kewarganegaraan atau sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian
lintas-bidang keilmuan, yang secara substantif ditopang terutama oleh ilmu
politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan secara pedagogis diterapkan
dalam dunia pendidikan persekolahan dan masyarakat. Secara filosofik tubuh
pengetahuan pendidikan kewarganegaran ini dilandasi oleh tilikan reconstructed
philosophy of education yang secara adaptif mengakomodasikan tilikan filsafat
pendidikan perennialism, essentialism, progressivism, dan recontructionism
(Brameld:1965). Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk kajian
lintas-bidang keilmuan ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar-formal
suatu disiplin (Dufty,1970 ; Somantri:1993) yakni mempunyai community of
scholars, a body of thinking, speaking, and writing; a method of approach to
knowledge dan mewadahi tujuan masyarakat dan warisan sistem nilai
(Somantri:1993). Ia merupakan suatu disiplin terapan yang bersifat
deskriptif-analitik, dan kebijakan-pedagogis. Jika dilihat dari pandangan Kuhn
(1970) secara paradigmatik, pendidikan kewarganegaraan baru memasuki
pre-paradigmatic phase atau proto science. Untuk dapat menggapai statusnya sebagai
normal science diperlukan berbagai penelitian dan pengembangan lebih lanjut
oleh anggota komunitas ilmiah “pendidikan kewarganegaraan” sehingga dapat
melewati proses artikulasi sosialisasi-pengakuan-falsifikasi-validasi-pengakuan
sebagai disiplin yang matured.
4.3. Missi
Secara konseptual “pendidikan kewarganegaraan” atau citizenship education
merupakan bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu sosial yang bersifat
“lintas-bidang keilmuan” dengan intinya ilmu politik, yang secara paradigmatik
memiliki saling-keterpautan yang bersifat komplementatif dengan pendidikan ilmu
sosial secara keseluruhan (Winataputra:1978, Barr dkk:1978, Welton dan
Mallan:1988, NCSS:1985, 1994, Somantri:1993). Dalam hal ini, bahwa (a) social
studies berpijak terutama pada konsep-konsep dan metode berpikir ilmu-ilmu
sosial secara keseluruhan, sedang citizenship education berpijak terutama pada
ilmu politik dan sejarah; (b) salah satu dimensi dari social studies adalah
citizenship education (NCSS:1994, CICED:1998), khususnya dalam upaya
pengembangan intelligent social actor (Banks:1977, NCSS:1994).Dalam konteks
proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi masyarakat madani
sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya, maka pendidikan kewarganegaraan
mengemban missi: sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis.
Missi sosio-pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan
Tuhan dan makluk sosial menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, demokratis,
taat hukum, beradab, dan religius. Missi sosio-kultural adalah memfasilitasi
perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praksis
demokrasi dalam koteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui
pengembangan partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggungjawab melalui
berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh dan
berkembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan. Sedangkan missi
substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan
pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan
generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue atau kebajikan
kewarganegaraan dan civic culture atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis
sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya
itu (fungsi aksiologis). Perwujudan ketiga missi tersebut akan memfasilitasi
pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai proto science menjadi disiplin
baru dan dalam waktu bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan
kualitas isi dan proses pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler
pendidikan demokrasi dan kegiatan sosio-kultural dalam koteks makro pendidikan
nasional.
4.4. Strategi
Secara konseptual-paradigmatik citizenship education saat ini mengembangkan
strategi dasar learning democracy, in democracy, and for democracy (CIVITAS
International:1998; QCA:1999; APCEC;2000). Kemudian strategi dasar ini oleh
QCA(1999) dikonsepsikan sebagai suatu kontinum education about
citizenship—education through citizenship—education for citizenship yang secara
kualitatif bergerak dari titik Minimal (education about citizenship) ke titik
Maksimal (education for citizenship). Pendidikan kewargnegaraan di Indonesia
yang dalam konteks internasional (Kerr:1999) dikategorikan kedalam kelompok
citizenship education Asia-Afrika yang masih berada pada titik Minimal yakni
education about citizenship sudah seharusnya menggunakan strategi progresif
menuju titik Maksimal, yakni education for citizenship melalui titik median
education through citizenship. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan sebagai
suatu academic endeavor (CICED:1999) atau sebagai bidang kajian dan
pengembangan pendidikan disiplin ilmu seyogyanya memusatkan perhatian pada
kajian ilmiah tentang civic virtue dan civic culture (Quigley:1991) atau
keberadaban dan budaya kewarganegaraan dalam konteks pengembangan civic
intelligence dan civic participation (Quigley:1991, Cogan:1999). Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah atau luar sekolah/di
perguruan tinggi di Indonesia, kedudukannya sebagai mata pelajaran/mata kuliah
yang berdiri sendiri perlu terus dimantapkan di semua jenjang pendidikan, agar
proses education about citizenship terwadahi secara sistimatik dan berbobot.
Pertimbangan tersebut juga dimaksudkan bahwa secara perlahan tetapi pasti,
melalui pemantapan mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan
penciptaan kehidupan sosila-kultural sekolah/ kampus yang demokratis, taat
hukum, religius dan berkeadaban, dapat dijalanai koridor sosial-kultural menuju
proses education for citizenship (konsep sekolah/kampus sebagai laboratory for
democracy. Dengan cara itu, pada saatnya nanti, para lulusan lembaga pendidikan
formal mampu menampilkan dirinya sebagai demokrat muda yang taat hukum,
religius dan berkeadaban dalam berbagai konteks kehidupan yang dijalaninya.
Namun demikian khusus dalam konteks pendidikan usia dini, yakni di taman
kanak-kanak dan sekolah dasar kelas rendah (1-3), karena perkembangan
psikososial siswa yang berada pada tarap kognitif concrete operation menuju
formal-operation (Piaget:1960) dan moralita pre-conventional morality yang
didominasi oleh punishment and obedience orientation meningkat ke good boy and nice
girl orientation menuju instrumental relativist orientation (Kohlberg:1975),
yang memerlukan keterpaduan dan kebermaknaan belajar dalam suasana yang otentik
atau hands-on experience, pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke
dalam mata pelajaran lain yang relevan dengan pendekatan cross-curriculum,
khususnya dalam pendidikan IPS, Bahasa dan kesenian, seperti mata pelajaran
Personal, Social, and Health Education (PSHE) di sekolah dasar di UK, Life
Orientation di Afrika Selatan dan Social Studies di negara lainnya.Sebagai
suatu bidang kajian pendidikan disiplin ilmu, sebagaimana juga citizenship
education, pendidikan kewarganegaraan diyakini secara konseptual memiliki sifat
multidimensional dalam aspek ontologis-obyek telaahnya, aspek epistemologis-metode
penelitian dan pengembangannya, dan aspek aksiologis-kemanfaatannya bagi dunia
pendidikan (Cogan:1996, 1999, CICED:1999). Sifat-sifat itulah yang mengikat
ketiga dimensi pendidikan kewarganegaraan dalam suatu paradigma yang utuh. Oleh
karena itulah pendidikan kewarganegaraan dapat disikapi dan diterima sebagai
suatu wahana sistemik atau integrated knowledge system atau synthetic
discipline dalam tataran filosofik dan konseptual pendidikan disiplin ilmu.
Jiwa dari paradigma ini diharapkan lebih menitikberatkan pada kearifan intuitif
yang beorientasi eco-action dan bersifat responsif, konsolidatif, dan
kooperatif daripada kekuatan rasionalitas yang beorientasi ego-action dan
bersifat agresif, ekspansif, dan kompetitif (Capra:1998). Dalam rangka pengembangan
sistem pendidikan kewarganegaraan dirumuskan strategi: (1) penegasan kedudukan
dan hubungan fungsional-interaktif antar ketiga sub-sistem pendidikan
kewarganegaraan (kajian ilmiah, program kurikuler, dan kegiatan sosio-kultural)
dan peran interaktif terhadap kompetensi kewarganegaraan; (2) pemanfaatan
secara adaptif-fungsional dari sumber-sumber konseptual dan empirik di luar
entitas sistem pendidikan kewarganegaraan.
Sebagai suatu domain kajian pendidikan ilmu, pendidikan kewarganegaraan
memerlukan kelembagaan yang berfungsi sebagai sarana institusional yang
memfasilitasi pengembangan epistemologi dan perwujudan aksiologi
kedisiplinannya, dan komunitas ilmiah yang berperan sebagai kelompok pemikir
wacana akademisnya dan pengembang sarana programatiknya. Oleh karena itu,
kedudukan jurusan atau program studi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan
tinggi perlu dimantapkan bukan semata-mata sebagai lembaga penghasil tenaga
kependidikan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai penghasil dan pengembang aspek-aspek
epistemologi, seperti nilai, konsep, prinsip, dan metode serta aneka ragam
program instruksional kewarganegaraan. Dalam konnteks itu maka selain program
profesional tingkat diploma dan S1, di perguruan tinggi sudah saatnya mulai
dikembangkan program akademik S2 dan S3 pendidikan kewarganegaraan.
4.5. Aspek Ontologis Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki dua dimensi ontologi, yakni obyek telaah dan obyek
pengembangan. Yang dimaksud dengan obyek telaah adalah keseluruhan aspek idiil,
instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan
eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PPKn di sekolah dan di
luar sekolah, serta format gerakan sosial-kutural kewarganegaraan masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan obyek pengembangan adalah keseluruhan ranah
sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan
psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warganegara,
yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai
kualitas warganegara yang “cerdas, dan baik, dalam arti demokratis, religius,
dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
4.6. Aspek Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan
Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan aspek
ontologi pendidikan kewarganegaraan, karena memang proses epistemologis, yang
pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya
membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan sudah
seharusnya terkait pada obyek telaah dan obyek pengembangannya. Kegiatan
epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan
metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan
pengetahuan baru melalui: (1) metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan
proses pengukuran dan generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi, dan
(2) metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap
fenomena alamiah untuk membangun suatu teori. Sedangkan, metodologi
pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa
kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta
didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan
kontekstual pendidikan.
Tercatat berbagai kegiatan epistemologis penelitian, pengembangan, dan
penelitian dan pengembangan. Yang khusus merupakan kegiatan penelitian antara
lain yang dilakukan oleh Capra (1998) tentang titik balik peradaban; Sanusi
(1998) tentang 10 pilar demokrasi Indonesia; Bahmueller (1996) tentang
perkembangan demokrasi; Welzer (1999) tentang konsep civil society; Gandal dan
Finn (1992) tentang education for democracy; Barr, Bart, dan Shermis (1977)
tentang konsep social studies; Remmers dan Radles (1960 dalam Shaver 1991)
tentang kesadaran politik dan hukum peserta didik; Stanley (1985) tentang
perkembangan social studies; Shaver (1991) tentang penelitian dan pembelajaran
social studies; Winataputra (1978) tentang pelaksanaan kurikulum PMP, CERP
(1972) tentang pemikiran mengenai pendidikan IPS dan kewarganegaraan; Cogan
(1996) tentang multidimensional citizenship education, ETS (1991) tentang
efektivitas program We the People … The Citizens and Constitution; Tolo dkk (1998)
tentang efektifitas program We the People… Project Citizens; Djahiri dkk (1998)
tentang profil kurikulum dan pembelajaran PPKN 1994, dan CICED (1999 dan 2000)
tentang konsep civic education for civil society dan tentang the needs for new
Indonesian civic education”.
Yang bersifat pengembangan kurikulum dan pembelajaran, tercatat antara lain
yang dilakukan oleh: Wesley (1937 dalam Barr dkk:1977) tentang definisi awal
social studies; Engle (1960 dalam Somantri 1993) tentang decision making dalam
social science instruction ; Hanna(1960) tentang pengembangan social studies
berdasarkan basic human activities ; Taba dkk (1970) tentang pendekatan spiral
of concept development dalam socialstudies; NCSS (1983) tentang scope and
sequence dalam social studies; NCSS (1989) tentang paradigma social studies
untuk abad 21; NCSS (1994) tentang standards for social studies; Dunn (1915
dalam Somantri:1969) tentang new civics ; CCE (1991) tentang dokumen akademis
CIVITAS: A Framework for Civic Education ; CCE (1997) tentang Paket Belajar We
the People … The Citizens and Constitution ; We the People… Project Citizen;
Law in a Free Society Series; Foundations of Democracy; CCE (1998) tentang
Paket Belajar Exercise in Participation. Sedangkan di Indonesia, yang termasuk
kegiatan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh: PPSP IKIP Bandung (1973)
tentang kurikulum IPS/PKN, Depdikbud (1974) tentang kurikulum IPS dan PMP 1975,
Depdikbud (1983) tentang penyempurnaan kurikulum PMP, Depdikbud (1993) tentang
kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Depdikbud (1999)
tentang pengembangan suplemen dan petunjuk teknis PPKn untuk masa transisi;
CICED (1999) tentang civic education content mapping. Yang termasuk kegiatan
penelitian dan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh: Bruner (1967)
mengenai model proyek pembelajaran Man: A Course of Study di Amerika Serikat;
dan Stenhouse (1975) mengenai humanities curriculum project di Inggris.
4.7. Aspek Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan
Yang termasuk ke dalam aspek aksiologi pendidikan kewarganegaraan adalah
berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang
kajianpendidikan kewarganegaraan yang telah dicapai, bagi dunia pendidikan,
khususnya pendidikan persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan.Hasil-hasil
penelitian dan pengembangan social studies, citizenship education dan civic
education” dalam dunia persekolahan banyak memberi manfaat dalam merancang
program pendidikan guru, meningkatkan kualitas kemampuan guru, meningkatkan
kualitas proses pembelajaran, meningkatkan kualitas sarana dan sumber belajar,
dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan.
5. Kesimpulan
(1) Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh atau sistem
pengetahuan yang memiliki: (a) ontologi civic behavior dan civic culture yang
bersifat multidimensional (filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural);
(b) epistemologi research, development, and diffusion dalam bentuk kajian
ilmiah dan pengembangan program kurikuler, prilaku dan konteks sosial kultural
warganegara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka
penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional
dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat;
dan (c) aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan body of knowledge sistem
pengetahuan atau disiplin pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan
memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan
luar sekolah; dan membingkai serta memfasilitasi berkembangnya koridor proses
demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat.
(2) Secara paradigmatik sistem pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga
komponen, yakni : (a) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b)
program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada
upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap
kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan.
(3) Secara kontekstual logika internal dan dinamika eksternal sistem
pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif
berupa Agama dan Pancasila; pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan seni;
cita-cita, Nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi; masalah-masalah
kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi
civic virtue dan civic culture untuk masyarakat madani Indonesia-masyarakat
negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional.
(4) Aspek esensial yang menjadi faktor perekat (integrating forces) dari
ketiga komponen sistem pendidikan kewarganegaraan sehingga membentuk suatu
kerangka paradigmatik yang koheren adalah konsep warganegara yang cerdas,
demokratis, taat hukum, beradab, dan religius yang dikristalisasikan menjadi 90
butir perangkat kompetensi kewarganegaraan (pengetahuan kewarganegaraan,
ahlak/sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) yang berkembang
secara dinamis.
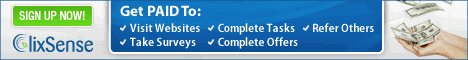




No comments:
Post a Comment
Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. jimmydj81.blogspot.com berhak menyaring Komentar yang akan ditampilkan.